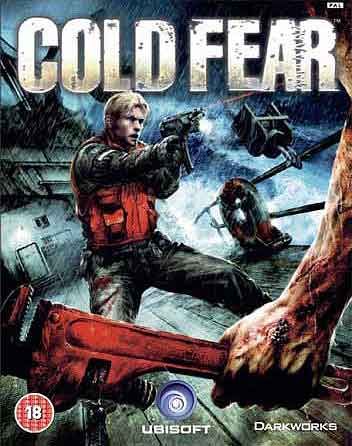Belakangan saya mulai merasa muak untuk mendengar berita dan melihat fenomena kekerasan akibat dari rasa kebangsaan dan terusiknya esensi keagamaan sebagai pembenaran terhadap tindak kekerasan, baik itu individu dan kelompok. Entah terlalu sering dibombardir media atau memang opini yang timbul malah lebih gila dibandingkan kenyataannya. Keyakinan yang disetir secara politis dipergunakan dalam kondisi yang tidak seragam, dan memang relatif gampang untuk mencapai sasaran. Dengan dalih agama dan dalih kesetiaan terhadap simbol negara, mereka meyakini tindakan represif atas nama kelompok dapat menunjukkan citra powerful dan merasa berhak membungkam kredibilitas hukum di negara ini yang memang sedang terpuruk.
Belakangan saya mulai merasa muak untuk mendengar berita dan melihat fenomena kekerasan akibat dari rasa kebangsaan dan terusiknya esensi keagamaan sebagai pembenaran terhadap tindak kekerasan, baik itu individu dan kelompok. Entah terlalu sering dibombardir media atau memang opini yang timbul malah lebih gila dibandingkan kenyataannya. Keyakinan yang disetir secara politis dipergunakan dalam kondisi yang tidak seragam, dan memang relatif gampang untuk mencapai sasaran. Dengan dalih agama dan dalih kesetiaan terhadap simbol negara, mereka meyakini tindakan represif atas nama kelompok dapat menunjukkan citra powerful dan merasa berhak membungkam kredibilitas hukum di negara ini yang memang sedang terpuruk. Padahal, dalam konteks kehidupan untuk bernegara, tindak kekerasan atau represi oleh masyarakat sangat tidak dibenarkan. Yang berhak melakukan represi ( dalam wujud ’netral’) adalah negara. Masalahnya, dalam pandangan sebagian masyarakat, logika seperti ini terasa berbelit-belit, sementara penyimpangan sosial sering terjadi. Serba salah, memang hal ini yang membuat kondisi makin terpuruk, bak buah simalakama. Buah simalakama mulai terkuak kembali dengan munculnya bibit krisis ekonomi yang mengakibatkan rusaknya tatanan hegemoni sosial ekonomi masyarakat.
Apakah karena memang harus melalui proses pembelajaran seperti ini?
Apakah kekerasan dan perilaku sosial kita sudah mulai runtuh?. Apakah karena rasa nasionalis (ekonomi perut) yang mengesampingkan nilai moral? Pengaruh orientasi hidup untuk materi lewat perlakuan tak seimbang dalam media komunikasi ?. Itulah identitas yang tercermin lewat rasa bangga berlebihan (over), dan kesatuan kelompok yang disalah gunakan, legitimasi palsu dalam wujud nasionalisme. Kebanggaan diwujudkan dalam simbol legitimasi sosial yang didukung oleh masyarakat tertentu. Toh, yang bertanggung jawab hanya seorang. Pembelajaran, seperti halnya seorang calon anggota mafia yang harus bertarung dengan puluhan orang untuk masuk kedalam keanggotaan kubu itu.
Apaan sih Nasionalisme itu?
Rasanya gampang, nasionalisme baru muncul kalau hal itu menyakut harga diri dan olahraga. Jujur saja, saya lihat rasa akan hal itu baru muncul jika ada sesuatu yang mengusik harga diri bangsa ini, dan pertandingan bulu tangkis atau PSSI di kancah Asia Tenggara. Nasionalisme adalah cangkang dari globalisme dalam lingkup paling kecil. Sedangkan Globalisme merupakan arena pencarian jati diri dalam suasana abstraksi yang tak bernyawa. Bagi mereka, globalisme telah memberikan arus dan celah masuknya intervensi budaya dan kultur asing yang sangat berbeda dari yang sudah ada. Alhasil, bagi mereka, globalisasi menciptakan era dingin tanpa norma dan pijakan sosial yang jelas, dalam konteks yang plural. Itulah yang melatari bagaimana saat ini, nasionalis yang timbul karena terusik, yang timbul karena balutan ekonomi, lapar dan kebencian dan rasa sensitifitas.
 Bagi beberapa golongan dengan latar belakang masyarakat yang berbeda dan tingkat pemahaman sosial yang cenderung berlawanan, sensitivitas akan arus perubahan sering disalah artikan dalam gerakan yang dilawan dalam segi fisik. Semua itu bisa jadi karena ketakutan terhadap arus, dengan mengedepankan pemahaman sempit dan ketakutan akan perubahan. Simbol legitimasi sebenarnya diperlukan oleh tiap kerumunan individu dalam satu wadah yang disebut masyarakat, untuk menentukan kearah mana mereka akan bergerak. Dalam hal ini wujud masyarakat bak anak ayam kehilangan induk sudah tergambar dalam hal ini. Salah kaprah dan cenderung mencelakakan individu lain.
Bagi beberapa golongan dengan latar belakang masyarakat yang berbeda dan tingkat pemahaman sosial yang cenderung berlawanan, sensitivitas akan arus perubahan sering disalah artikan dalam gerakan yang dilawan dalam segi fisik. Semua itu bisa jadi karena ketakutan terhadap arus, dengan mengedepankan pemahaman sempit dan ketakutan akan perubahan. Simbol legitimasi sebenarnya diperlukan oleh tiap kerumunan individu dalam satu wadah yang disebut masyarakat, untuk menentukan kearah mana mereka akan bergerak. Dalam hal ini wujud masyarakat bak anak ayam kehilangan induk sudah tergambar dalam hal ini. Salah kaprah dan cenderung mencelakakan individu lain. Kekerasan dengan kelompok ?
Ini merupakan sebuah indikasi nyata bahwa anarki sosial yang terjadi di ruang-ruang publik sulit melepaskan diri dari simbol, idiom dan atribut bahkan keyakinan yang disandang oleh para pelakunya. Dengan kata lain, anarki sosial dalam konteks individu amat sangat berbahaya karena erat dengan tindakan kriminal, sedangkan kekerasan (secara sadar) yang dilakukan atas nama kelompok merupakan sebuah pertunjukan kesenjangan cita-cita (das Sollen - kalo kata Hegel) dengan kenyataan.
Kenyataan untuk hidup yang hakiki dan saling menghormati dihantam oleh pemahaman keyakinan yang dangkal dan cenderung gampangan, sehingga dirinya merasa berhak melukai orang lain tanpa merasa perlu untuk bertanggung jawab.

 Jika Hitler men-setting setiap pidato banner-banner raksasa bergambar swastika, untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan Bangsa besar a la NAZI, dan tema kerakyatan atau
Jika Hitler men-setting setiap pidato banner-banner raksasa bergambar swastika, untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan Bangsa besar a la NAZI, dan tema kerakyatan atau  Dan selanjutnya, realisme sosialis yang dulu dimanfaatkan sebagai propaganda masih hidup di Rusia,Cina dan bahkan negara-negara lain, mungkin masih ada sebagai sebuah artefak namun juga sudah "memfosil" dan hampir mati.
Dan selanjutnya, realisme sosialis yang dulu dimanfaatkan sebagai propaganda masih hidup di Rusia,Cina dan bahkan negara-negara lain, mungkin masih ada sebagai sebuah artefak namun juga sudah "memfosil" dan hampir mati. Sebelum Aidit ada pula Dharsono dan Sema'un. Bagaimana Saudara Nyoto ? Wikana dan lainnya. Dan juga, kalau organisasi Komunis Indonesia, merupakan buah pikiran dan upaya Almarhum
Sebelum Aidit ada pula Dharsono dan Sema'un. Bagaimana Saudara Nyoto ? Wikana dan lainnya. Dan juga, kalau organisasi Komunis Indonesia, merupakan buah pikiran dan upaya Almarhum  Saya mengenang saat itu, saya masih tidak pernah berani menonton sampai selesai, berikut juga; layar buram (karena terlalu sering diputar), darah dan kekejaman digambarkan secara gamblang. Bibir hitam tebal mengepulkan asap tembakau yang mengucapkan kalimat seperti; " ..Jawa adalah Kunci..", " Darah itu merah, jendral!" dan lain sebagainya. Ada juga irama musik genjer -genjer dan ini yang terpenting; GERWANI. Ada pula semboyan egaliter, " Sama rata!". Sebuah semboyan yang meniadakan wujud fisikal makna kata; "lebih" dan kelebihan dalam proporsi yang merata. Sehingga terciptalah kesan bahwa Komunis memang dibentuk menjadi menakutkan dan banyak yang merasa sedikit angker untuk menelusuri jejak bangkai salah satu partai terkuat di Indonesia ini dahulu, semua diakibatkan oleh besarnya dendam berdarah-darah puluhan tahun para pelaku dan turunannya. Semua dikonstruksikan sebagai tindakan kejam tak berperikemanusiaan dengan kredo agama, dan pemberontakan yang mengganggu asas kemerdekaan.
Saya mengenang saat itu, saya masih tidak pernah berani menonton sampai selesai, berikut juga; layar buram (karena terlalu sering diputar), darah dan kekejaman digambarkan secara gamblang. Bibir hitam tebal mengepulkan asap tembakau yang mengucapkan kalimat seperti; " ..Jawa adalah Kunci..", " Darah itu merah, jendral!" dan lain sebagainya. Ada juga irama musik genjer -genjer dan ini yang terpenting; GERWANI. Ada pula semboyan egaliter, " Sama rata!". Sebuah semboyan yang meniadakan wujud fisikal makna kata; "lebih" dan kelebihan dalam proporsi yang merata. Sehingga terciptalah kesan bahwa Komunis memang dibentuk menjadi menakutkan dan banyak yang merasa sedikit angker untuk menelusuri jejak bangkai salah satu partai terkuat di Indonesia ini dahulu, semua diakibatkan oleh besarnya dendam berdarah-darah puluhan tahun para pelaku dan turunannya. Semua dikonstruksikan sebagai tindakan kejam tak berperikemanusiaan dengan kredo agama, dan pemberontakan yang mengganggu asas kemerdekaan. Sehingga, pada akhirnya, pertikaian tentang ujung pangkal sejarah, dekonstruksi dan penyajian dilibatkan kedalam inteprestasi masing-masing yang memanfaatkan kekuatan media, citra dan ideologi bentukan masa kini. Toh, ideologi berakhir pada harkat manusia, dan imajinasi diri sendiri. Dan tak lupa lewat doktrin tentunya.
Sehingga, pada akhirnya, pertikaian tentang ujung pangkal sejarah, dekonstruksi dan penyajian dilibatkan kedalam inteprestasi masing-masing yang memanfaatkan kekuatan media, citra dan ideologi bentukan masa kini. Toh, ideologi berakhir pada harkat manusia, dan imajinasi diri sendiri. Dan tak lupa lewat doktrin tentunya. Syahdan, di tahun 85 atau 86,
Syahdan, di tahun 85 atau 86,  Kelaparan memang sangat tidak enak, sangat menyedihkan, menyakitkan bisa jadi buah penyakit konspirasi akut penopang kehidupan sosial. Baik itu kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan kehidupan yang layak serta harga bahan pangan dan sandang yang mahal. Apakah kemudian kita masih mempunyai otoritas untuk mempertanyakan apakah keadilan yang seperti ini layak untuk mengetengahkan apa yang disebut kehidupan pada saat ini?
Kelaparan memang sangat tidak enak, sangat menyedihkan, menyakitkan bisa jadi buah penyakit konspirasi akut penopang kehidupan sosial. Baik itu kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan kehidupan yang layak serta harga bahan pangan dan sandang yang mahal. Apakah kemudian kita masih mempunyai otoritas untuk mempertanyakan apakah keadilan yang seperti ini layak untuk mengetengahkan apa yang disebut kehidupan pada saat ini?